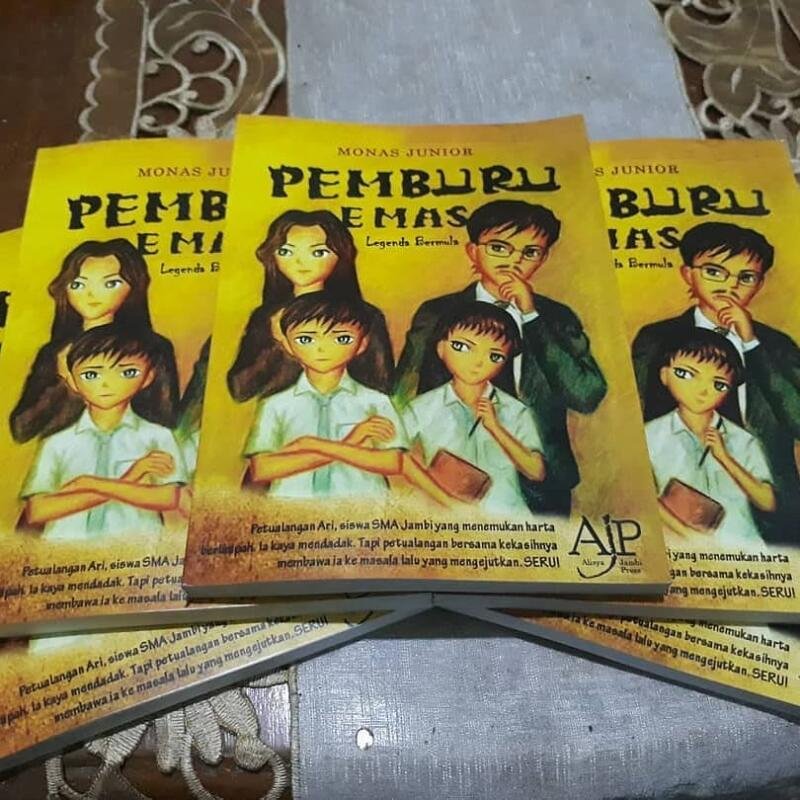Perjalanan kami berhenti di Desa Siau. Kata sopir, kalau mau mencapai Jangkat harus pakai motor trail atau naik kuda. Aku awalnya tak percaya, tapi setelah melihat kondisi jalan, aku langsung setuju. Jalan tanah merah selebar satu mobil terhampar di tanah pebukitan. Bisa dipastikan kalau hujan tanah ini menjadi sungai lumpur dan kalau panas seperti saat ini menjadi aliran debu. Aku tetap harus sampai di sana, karena itu kusewa satu motor trail lengkap dengan pengendaranya.
Pemanduku bernama Bang Arif. Dia yang mengantarku menembus jalan sadis penuh ancaman itu. Aku makin merinding ketika kami melalui jalan gelap dengan pepohonan raksasa di kanan kiri jalan.
“Jangan bicara, nanti Datuk marah.” Bang Arif mengingatkan dengan nada tegang.
Setiba di Jangkat, aku baru dikasih tahu Bang Arif soal Sang Datuk. Bagi warga setempat, Datuk adalah panggilan kehormatan bagi Harimau. Ya, Harimau Sumatera. Binatang penguasa rimba itu sering terlihat menyeberang di jalan kawasan hutan lindung, tempat di mana beberapa jam lalu kami lewati. Aku langsung mengucap sukur kepada Tuhan karena kami tak dipertemukan dengan Sang Datuk. Apalagi kami melalui hutan pekat itu di malam hari, benar-benar bencana jika betemu beliau di sana.
Atas saran Bang Arif, akhirnya aku bermalam di rumah makan milik Wak Badar. Di sini tidak ada hotel atau penginapan. Padahal, cuaca dan pemandangannya bisa disamakan dengan Kota Bogor atau Bandung. Dingin, berlatar gunung dan pebukitan, hamparan sawah di mana-mana, menjadikan Jangkat sebagai destinasi wisata yang patut dikunjungi.
Setengah sebelas menjelang siang, di depan warung, aku menyambut matahari pertama dengan heran. Hari sudah mulai tinggi, tapi mulutku masih mengeluarkan embun seperti asap mengepul setiap kali berbicara atau menghembuskan nafas. Kau tahu, dinginnya membuat tujuh lapis pakaian tak menghasilkan hangat sesuai yang diinginkan. Tetap saja aku menggigil setiap kali Wak Badar menawarkan kopi asli kampung ini walau disertai senyumnya yang hangat. Bang Arif sudah dari subuh tadi balik ke Siau, tanpa meninggalkan kulitnya yang tebal itu untukku bertahan di tempat ini.
Barulah sekitar jam dua siang, setelah matahari berhasil menguasai dingin, aku dan Wak Badar berjalan mengitari desa hingga akhirnya berhenti di desa terujung, Talang Tembaga. Sementara Wak Badar masih di motor, aku berdiri menatap bukit yang berada cukup jauh dari desa ini.
Wak Badar turut memperhatikan bukit itu. “Kampung Emeh (Emas) kata orang sini. Kalau mau ke sana, besok saja. Bisa dua hari dua malam jalan kaki menuju bukit itu.”.
Aku cuma bisa mengangguk pelan. Tampaknya matahari belum sepenuhnya menguasai dingin. Kulit-kulit jariku masih berkeriput seperti habis mandi di kolam es. Kami kembali ke warung. Di dapur dekat dengan tungku kayu yang masih membara, akhirnya aku bisa bernafas lega. Hangatnya bara kayu mengurangi kerut-kerut di jariku.
Wak Badar yang berusia hampir 60 tahun itu mulai bercerita tentang tambang emas peninggalan Belanda di bukit itu. Katanya, dulu, orang Belanda berhasil mendapatkan berton-ton emas dari tempat itu. Bahkan dia mendengar satu gua bekas galian Belanda yang sekarang sudah tertimbun tanah.