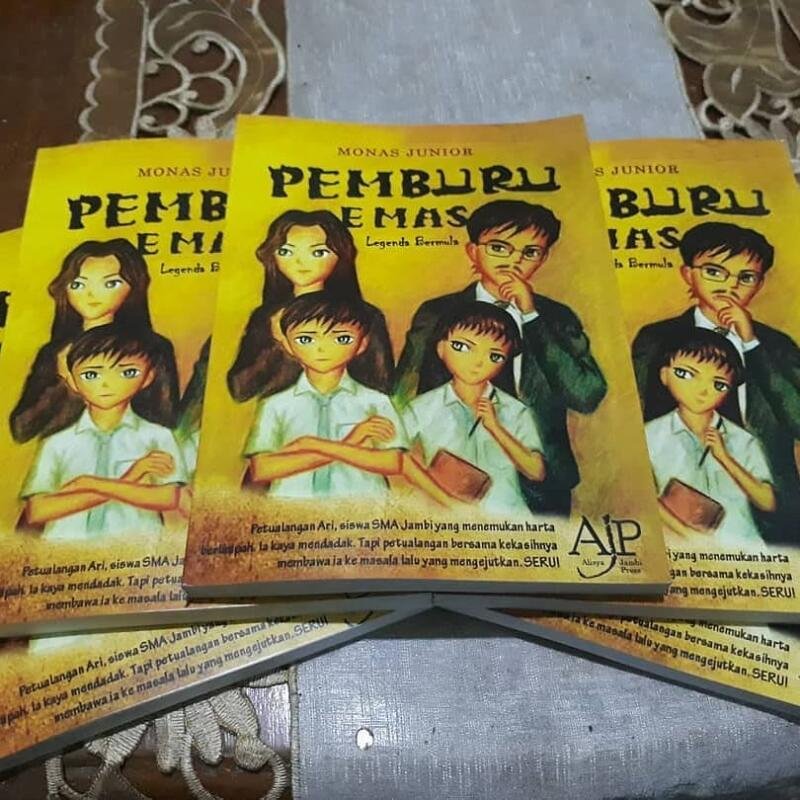“Aku, Hati dan Pasukan Cupid yang bertekuk lutut di kakimu”
Baiklah. Sudah pagi lagi. Anas merasa beruntung karena ia telah mengalahkan matahari pertama hari ini sejak dua jam lalu.
Di indekos yang sama, di atas tunggangan yang sama, memakai celana blue jeans yang sama hanya beda kemeja saja, serta keruwetan menyisir rambut keriting panjang yang sama, Anas meluncur pelan dari teras kostannya ke jalan protokol.
Targetnya masih sama, bertemu Pak Mus, Ketua Yayasan kampus yang ingin dilobinya.
Sepagi ini, jalan-jalan protokol penuh sesak. Semua berebut ingin cepat sampai di tujuan masing-masing.
Kembali di simpang empat kemarin, Anas bernafas lega karena ia ingat di mana harus menaruh helm ketika polisi kemarin menatapnya pangling. Ia melempar senyum, tapi polisi itu terlalu sibuk untuk memperhatikan keramahannya.
Lampu hijau. Anas memacu Jupiter umur setahun itu dengan santai. Dibiarkannya mobil-mobil, motor-motor dan kerutan kening para pengendara mendahuluinya. Bagaimanapun, ia terlalu pagi hari ini.
Jarak 10 kilometer dari Anas, Neneng sedang sibuk memasang sepatu kets hitam, menyandang tas katun warna pink, lalu bersama gadis kurus tinggi 1,6 meter berjalan cepat ke luar teras rumah dua pintu.
“Adek kalau pulang telepon dulu, soalnya Ayuk mau ke pasar sebelum ke rumah,” Neneng memandang ke Mila, adiknya yang masih kelas 1 SMA.
“Tapi ndak lama kan, Yuk?”
“Ndak. Paling jam dua sudah di rumah.”
“Mila nunggu di rumah kawan dekat sini aja ya.”
“Ya lah.”
Mereka berdua sampai di simpang lorong. Menyeberang jalan yang dipenuhi mobil-motor, keduanya berpisah dengan salam cium tangan dari Mila ke Neneng.
Neneng menoleh sejenak ke arah adiknya yang sudah bertahun-tahun didera sakit paru-paru itu. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca membayangkan betapa sengsaranya gadis manis itu setiap kali mau tidur.
“Yang sabar ya, Dek,” lirihnya dalam hati.
Mobil angkot warna biru yang ditungguinya berhenti. Bergegas naik, ia duduk dan berharap adiknya bisa menjalani hari ini dengan ringan, seringan embun yang terangkat matahari pagi.
Sampai di kampus yang sudah penuh dengan mahasiswa sedang memarkirkan motor, Neneng merangsek masuk ruang sekre Kesenian. Ia periksa proposal kemarin yang diketiknya, ternyata file-nya masih ada di komputer. Lega, ia bergegas ke arah tangga bagian dalam kampus, melintasi Anas yang sibuk mengetik SMS di ponselnya.
Keduanya saling tak sadar sudah bersua, tapi saking sibuknya dengan target masing-masing, pertemuan itu jadi tak bermakna. Dua cupit terlihat bersedih di atas kepala keduanya.
Tiba di lantai 2, Neneng mencari sahabat-sahabatnya. Ah, rupanya di sana, tepat di pintu masuk ruang tengah dari 10 ruang lantai 2.
“Pagi Lus, Lot, Ma,” Neneng menyapa ceria.
Ketiga sahabatnya menyapa lebih ceria lagi. Tawa-tawa ringan mereka mengisi suasana pagi di kampus ungu yang sibuk itu.
Sedang di lantai 1, Anas mengumpulkan keberanian untuk mengetuk ruang bagian administrasi kampus.
Tujuh tahun. Ya, tujuh tahun sudah ia tak menginjak ruang ini. Ruang suci yang hanya mahasiswa tertentu saja yang bisa memasukinya. Kalau tidak penerima beasiswa, tentu yang bermasalah.
Ia adalah yang terakhir. Bermasalah karena sudah 7 tahun tidak masuk kampus. Tak hadir di tiap mata kuliah meski selalu bayar uang semester.
Ini adalah kali kedua ia bertemu dengan Pak Mus. Setelah sebelumnya, ia memohon-mohon agar tidak dikeluarkan dari kampus kepada Pak Mus. Bersukur pria bertubuh kekar itu mau mengampuninya hingga akhirnya menjadwalkan pertemuan di hari kemarin.
Anas berharap masih bisa bertemu dengan penguasa kampus itu meski kemarin tak berhasil bersua.
Tok! Tok! Tok!
“Masuk!”
Suara perempuan.
Anas perlahan membuka pintu, melongokkan kepala ke dalam, lalu masuk dua langkah. Menutup pintu, kemudian berjalan menghampiri ibu Neti, dosen Logika Algoritma yang mematikan.
“Anas?”
“Pagi, Buk.”
“Ke mana aja kamu? Sekarang sudah kerja? Perasaan ndak pernah lihat kamu wisuda, Nas.”
“Memang belum, Buk.”
“Hah?”
Bu Neti menganga. Sepagi ini hanya ada wanita bertubuh tambun ini di ruang yang makin lama makin menyeramkan bagi Anas.
“Pak Mus ada, Buk? Sudah janjian kemarin.”
“Oh. Ada. Tunggu, ya.”
Bu Neti mengetuk pintu kaca di bagian belakang ruang itu. Tubuhnya menghilang sesaat, lalu muncul lagi dari balik pintu sambil membawa senyum yang lebih mirip rengutan.
“Masuk.”
“Makasih, Buk.”
Di dalam, pria berambut pendek klimis sisir kanan yang mengenakan baju safari krem menatapnya dengan tajam. Kedua mata, kerongkongan, hingga jantung Anas nyeri seketika.
“Duduk.”
“Pagi, Pak.”
Pak Mus meletakkan dua tangannya di atas meja kaca hitam.
“Masih mau lulus?”
“Masih, Pak.”
“Kan kamu sudah kerja. Buat apa titel?”
“Eee…”
Pertanyaan menbagian depank yang tak bisa dijawabnya. Benar-benar serangan telak buat otaknya yang beku ketakutan.
“Kamu kan sudah jadi wartawan. Pasti wawasan dan pergaulannya lebih luas dari kami-kami di kampus ini. Ya, kan?”
“Eee… bukan gitu, Pak. Saya…”
Ah, mata tajam itu, benar-benar berhasil melukai lidah Anas.
“Saya sudah dihubungi Bang Ucok. Dia sudah jelaskan ke saya tentang kamu.”
Ah, Bang Ucok, senior di kantor yang sangat baik hati.
“Jadi, gimana, Pak?”
“Kamu harus kuliah lagi. Masuk dari semester 1, sampai semester 5.”
“Maksudnya, Pak?”
“Saya sudah lihat mata kuliah kamu yang sangat banyak tertinggal itu. Solusinya, kamu harus ikuti setiap mata kuliah di tiap tingkatan. Hanya itu.”
“Jadi, harus semua kelas di semua tingkatan saya masuki, Pak?”
Pak Mus mengangguk tegas. Anas merengut pula dengan tegas.
“Sanggup?”
“Sanggup, Pak.”
Tidak sanggup! Jerit hati Anas meronta-ronta ingin dilepaskan keluar dan menonjok muka pria semrawut yang sok-sokan itu.
Di ruang sekre Kesenian, Anas mencari-cari Didit, satu-satunya adik leting dan sahabatnya yang tersisa di antara ratusan seletingnya di kampus ungu ini. Tapi Didit tak ada di situ. Ia berjalan ke lantai 2, mengintip dari balik jendela kaca satu per satu ruang kelas yang penuh diisi anak-anak yang sedang ujian semester. Lagi-lagi Didit tak ditemukan.
Capek, masih di lantai 2, Anas duduk di salah satu kursi depan ruang paling pojok sebelah kanan. Ruangan yang persis berada di atas ruang sekre Kesenian.
Matanya terpejam sementara otaknya makin panas memikirkan setahun ini harus keluar masuk kelas dari pagi sampai malam hari. Baik reguler maupun kelas non reguler, terpaksa harus dimasukinya demi mengejar puluhan mata kuliah yang terlewatkan 7 tahun terakhir ini.
Anas mengurut keningnya yang berdenyut-denyut dengan tangan kanan. Saat tangannya dilepas, Gadis Mungil yang Cantik itu tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu.
Kemeja putih lengan panjang, rok hitam selutut, sepatu hitam berkaos kaki putih, rambut hitam sebahu dibando putih, membuat semua beban di tubuh Anas melayang diangkat matahari yang mulai menua.
Lima menit lebih ia hanya terpukau menatap Gadis Mungil yang Cantik itu. Di menit berikut barulah diberanikannya diri untuk menyapa pasangan hatinya itu.
“Dek. Jam berapa sekarang?”
Gadis itu kaget. Menatap Anas sesaat, lalu beralih ke jam tangan berkulit hitam di tangan kanannya yang berbulu halus.
“Jam 10, Kak.”
Ia menatap Anas lagi. Kali ini Anas menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena hatinya dan pasukan Cupid bersekongkol ingin menaklukkan diri di tapak kaki Gadis Mungil yang Cantik itu. Benar-benar bertekuk lutut.
“Makasih, ya.”
Neneng hanya tersenyum. Tapi senyum yang tidak “hanya” buat Anas.
“Dek.”
“Ya, Kak.”
“Boleh minta nomor HP? Kakak mungkin nanti masuk kelas Adek. Jadi kalau perlu info kuliah, Kakak telpon Adek, aja.”
Lagi-lagi Neneng tersenyum. Senyum dikulum yang menawan. Unik. Aneh. Tapi membahagiakan.
“Kakak sudah jarang lihat cewek sekarang pakai rok. Adek cantik sekali pakai rok kek begini.”
Teng. Tiba-tiba keberanian Anas muncul. Hati dan pasukan Cupid berhasil mempropokasi dirinya.
Lagi-lagi senyum itu, senyum yang meluluhlantakkan.
“Nomor HP?”
Setengah memaksa, Anas mengeluarkan HP-nya. Lalu mencatat angka-angka yang disebut Neneng. Usai itu, sudah.
Keberanian dari hati dan pasukan Cupid hanya sebatas itu.
Usai memasukkan HP ke dalam kantong celana, Anas meninggalkan gadis itu di tempat yang semula bersama separuh hati, separuh jiwa dan separuh masa depan yang tersia-siakan. Cupid di atas kepalanya menangis sejadi-jadinya.
Ujian selesai. Keramaian menjadi-jadi di kampus ungu begitu semua mahasiswa yang berada di lokal masing-masing keluar secara bersamaan.
Anas kembali ke ruang sekre, sedang Neneng kembali ke rangkulan sahabat-sahabatnya.(Bersambung ke page berikut)
Bahar 2006, sore menjelang Magrib.
Hutan pohon sawit menutupi sebagian besar kawasan kecamatan terluas di Kabupaten Muaro Jambi ini. Jalan berlubang dengan sisa aspal mengelupas digilas motor dengan pengendara berhelm balap merah, rambut panjang keriting yang menyembul di bagian belakang helm melambai-lambai diterpa angin, jaket kulit hitam, celana jeans hitam dan sepatu jungle hitam.
Hanya 30 kilometer per jam lari motor itu, tapi cukup membuat gerombolan monyet yang duduk di atas beberapa pohon sawit tepi jalan berhamburan. Seekor induk burung balam bersama lima anaknya ikut-ikutan kabur ke bagian dalam kebun sawit mendengar deru motor 4 tak itu.
Menembus barisan pohon sawit, motor Jupiter dengan tuannya yang tak sabaran itu akhirnya tiba di pemukiman penduduk. Rumah-rumah sisa program transmigrasi presiden zaman orde lama; berdinding-dinding papan, atap seng, tinggi 2,5 meter, pagar kayu, pekarangan luas dengan berbagai pohon buah di dalamnya, masih terlihat di tepi-tepi jalan beraspal serampangan itu.
Terus masuk sekitar setengah kilometer, tampak pasar rakyat yang jauh lebih modern. Bangunan beton di kanan-kiri jalan menyambut dengan ramah. Motor-motor berkeliaran di jalanan yang berdebu tebal. Dinding-dinding bangunan yang menguning diselimuti debu, kembang-kembang yang semuanya berwarna kuning akibat debu, dan wajah-wajah berbedak debu, memperhatikan motor Jupiter hitam yang perlahan-lahan berhenti dan parkir di salah satu warung kopi.
Sang pengendara bertinggi 170 cm turun. Dipasangnya kaki motor, dilepasnya helm -rambut panjang keritingnya terurai bebas- lalu digantungnya di spion, kemudian berjalan ke arah seorang pria -tinggi 150 cm, kulit agak hitam, rambut pendek, muka bulat, dan tubuh agak gemuk, mengenakan baju kaos oblong merah dan celana jeans biru bersendal jepit- yang berdiri menyambutnya di muka pintu warung.
“Oi Nas! Sampai juga akhirnya.”
Pria berwajah keras itu menyambut dengan lembut.
“Ayo, ngopi dulu. Masuk masuk…”
Digiringnya Anas ke dalam warung. Tiga pria bertubuh atletis di dalam warung langsung berdiri dan cepat-cepat keluar setelah mengangguk cepat ke pria berwajah keras itu. Mereka duduk bersebelahan di kursi kayu panjang 2 meter.
“Bang Des, Pak Kades ada?”
Andes menggeleng. Dilambaikannya tangan kiri ke penjaga warung di belakang, lalu ditunjuknya ke gelas kopinya yang sudah kering, kemudian mengisyaratkan 2 jari ke penjaga warung. Bapak penjaga warung berusia 60-an tahun itu mengangguk cepat.
“Pak Kades kayaknya takut sama kamu. Waktu kubilang kau akan datang, dia langsung gugup.”
“Gitu ya, Bang. Aku sempat nelpon dia tadi sebelum ke sini.”
“Mmm… pantas. Lain kali jangan bilang ke dia, cukup kasih tahu aku aja.”
“Siap salah, komendan!”
Andes tertawa lepas.
Dua gelas kopi tiba. Embun tipis mengepul dari sisa penyubliman air panas dari dalam gelas kaca bening itu.
“Kamu dari mana baru sampai ke sini Magrib. Bukannya kamu bilang siang sudah sampai Bahar?”
Anas memiringkan tubuh menghadap ke Andes. Lalu bercerita perjalanannya dari Kota Jambi ke Bahar jam 2 siang. Sampai di Bahar jam 5 sore, ia mampir ke proyek pembangkit listrik di desa sebelah. Wawancara pekerja dan masyarakat sekitar, mengambil foto lalu meluncur ke sini, warung kopi sederhana di tengah pasar.
“Di sana ada masalah, gak?”
“Aman, Bang. Setelah kusebut nama Abang ke pekerja, mereka langsung wellcome.”
Lagi-lagi Andes terkekeh.
“Pandai kali kau muji orang.”
Gantian Anas tertawa lepas.
Mereka menyeruput kopi sambil sesekali membahas pembangkit listrik yang sekarang jadi garapan utama di kejaksaan tinggi Jambi itu. Ada dugaan markup atau penggelembungan dana pada proyek tersebut. Keterlibatan pejabat sampai kepala daerah makin hari makin terlihat. Ini membuat Anas harus turun langsung ke lokasi untuk mencari tahu lebih banyak, dan mengumpulkan data untuk diterbitkan oleh korannya esok pagi.
Ah, esok pagi.
“Bang, saya harus balik lagi ke Jambi. Ngejar deadline.”
“Eh, nanti lah. Makan dulu…”
“Di Jambi aja, Bang. Takut ndak terkejar ngetik beritanya.”
“Ya kalau begitu mau apalagi lah aku.”
“Nanti kita kontak-kontak ya, Bang.”
“Siap komendan!”
Anas tertawa sambil berjalan ke motornya.
Setelah semua dirasa siap, Anas berpamitan. Andes melepas dengan lambaian tangan kaku.
Magrib telah tiba saat Anas melewati pohon-pohon sawit tanpa lampu jalan. Hanya temaram lampu dari motornya yang menembus jalanan terjal Bahar yang masih rawan tindak kriminal itu.
Sementara di waktu yang sama, 70 kilometer dari Bahar, Kota Jambi sedang terang-terangnya dihiasi lampu-lampu.
Mal di tengah-tengah pasar, makin lama makin ramai dipenuhi pengunjung. Mobil-motor tampak antri di gerbang masuk. Tapi karena parkiran penuh, pengunjung banyak memilih keluar lagi dari mal di tepi Sungai Batanghari itu.
Di dalam, lantai 1, panitia lomba puisi sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya jelang perlombaan dimulai. Neneng duduk di antara peserta lain. Wajahnya tirus bermata sipit, hidung bangir, bibir tebal ber-lipsgloss bening, menatap ke depan sambil komat-kamit menghapal puisi yang akan dibacakannya.
Dua panitia perempuan di atas panggung menyiapkan mic dan merapikan meja-kursi dewan juri. Tapi sayang, sampai jam segini, tiga juri belum juga tiba.
Neneng berdiri sambil merapikan blus hijau lengan pendeknya, mengeluarkan hp lalu menelpon seseorang. Saat itulah juri yang dinanti-nanti datang. Seorang wanita dan dua pria. Pria yang satu berambut gondrong sebahu dengan kemeja kusut.
Ketiganya disambut panitia, lalu duduk di kursi panggung. Satu per satu peserta dipanggil untuk tampil. Neneng melihat ke nomor di bagian depannya, 50, masih lama gilirannya.
Dua jam kemudian, ia tampil. Belum mulai membacakan puisi, seorang lelaki gondrong mendatangi juri yang juga berambut gondrong. Setelah berbisik-bisik sebentar, juri yang gondrong sebahu duduk lagi sementara si gondrong yang datang itu mengambil posisi berdiri di belakang panggung.
Neneng mengatasi rasa gugupnya. Tapi tak berhasil. Dadanya sesak dengan desakan mata-mata yang tertuju tajam ke arahnya.
MENERIMA BINGKISAN WAKTU
Oleh :
Ari Setya Ardhi
barangkali aku telah melupakan
waktu yang tergolek di atas
kelembutan almanak. ketika tiba-tiba
samudera tanggalan itu meledak
di atas kesunyian. dinding-dinding retak
mengalirkan embun dari luar rumah,
kasur dan bantal menggigil.
di kebeningan lantai marmer ada
kesakitan darah mengalir, mencercahkan
bayang-bayang pertikaian yang
selalu kita serukan berulang-ulang.
menyesali kehadiran hari sembari
menghitung keriuhan pasar yang terus
saja bertumbuhan memadati terminal
benak, membebaskan kemerdekaan bergulat
dengan berbagai berita atau
sedikit bahasa asmara yang
meluluhlantakkan nama-nama sajak
dari tiap detak jam kamarku
ah, kesibukan itu bukan aroma kehilangan
hanya pijar kerelaan yang harus dituntaskan!
pagi itu kuterima bingkisan waktu
tanpa menemukan jejak pengirim,
karena kantor pos telah lupa
membaca alamat-alamat yang
berserakan dalam rahim pabrik-pabrik,
super market dan swalayan
mengalirkan kelelahan angka-angka
yang telah menjadi kepengapan dalam
kepenatan hotel-hotel. kemudian
mimpi-mimpi itu menjelma kepedihan
yang harus ditebus dengan memeram
dendam, membungkus luka dengan
percikan ombak sembari menekan
kelalaian tanggalan ke dasar lentera laut
hingga kebosanan itu mampu
merapat pinggir pesisir atau
sekedar menyentuh pasiran pantai, meski
selalu saja peradaban kemudi
sampanku melarutkan dermaga,
sementara sauh di bagian depan menampar-tamparkan
tsunami dengan lidah api
terjulur mengecam kedamaian
yang hanya menjadi kebiasaan yang
lalu lenyap dibantai keterbatasan
pelayaran rinduku bagai perjalanan
tanpa peta-peta kehidupan,
memperpendek skala kematian
memasuki kekufuran dosa-dosa
yang terlanjur menjadi barang dagangan
maka, aku hidupkan dunia mimpi
memilih kelelapan surga yang ditawarkan.
Bohemian Jambi, 5 Mei 2000
Penonton bertepuk tangan begitu Neneng mengakhiri bacaan puisinya. Bahkan tiga juri mengangguk-angguk dan bertepuk tangan pula untuknya. Neneng tersenyum. Ia sangat bahagia.
Begitu turun panggung, lelaki yang berdiri di balik panggung tadi menghampirinya. Tubuhnya yang bau keringat bercampur debu membuat Neneng menggeser badan ketika lelaki itu duduk di sebelahnya.
“Mantap, Dek.”
Neneng tak menjawab. Ia rasa-rasa kenal dengan pria kumal di sebelahnya ini.
“Kak Anas. Kita sekampus. Yang kemarin kenalan di lantai 2.”
Neneng melirik sebentar, lalu mengerutkan kening.
“Tak apa kalau lupa.”
Anas pasrah. Hatinya luka.
Tapi Neneng mau buat apa? Ia sama sekali tak menyimpan memori perkenalan di lantai 2 itu.
“Kami duluan ya, Kak.”
“Pulang sama siapa?”
“Sama Adek. Di luar.”
Neneng buru-buru meninggalkan lelaki kurus itu. Anas terpaku. Lagi-lagi Cupid di kepala Anas dan Neneng menangis sejadi-jadinya.
Anas hanya mampu menatap dari tempat berdirinya saat Neneng menghilang dari balik pintu kaca mal itu.
“Woi!”
Anas kaget ketika seseorang menepuk keras bahu kirinya. Ia berbalik badan.
“Bos Cekgu. Bikin kaget aja.”
“Siapa tu?”
“Kawan sekampus.”
“Ooo… Baca puisinya bagus.”
Salah satu juri lomba puisi ini memuji Neneng, Gadis Mungil yang Cantik kepunyaan hati Anas itu.
“Bisa dimenangkan, ndak Bos?”
“Mau nyuruh juri kolusi? Orde lama sudah lewat, Bos!”
Keduanya tertawa keras sampai-sampai semua pengunjung mal yang ada di dekat mereka terheran-heran.
Malam di Kota Jambi ditutup padamnya sekian banyak lamu di gedung-gedung dan rumah-rumah penduduk. Hanya lampu jalan yang masih setia menghiasi kota Tempoyak ini.
Sampai di rumah, Anas disambut Nda, adiknya yang baru pulang dari kampung. Tubuhnya begitu lelah sampai-sampai tak sempat lagi bercerita banyak dengan adiknya yang kuliah di Unja itu.
Di rumah kontrakan dua pintu, tak jauh dari kosan Anas, Neneng sedang berbaring sambil membayangkan betapa hebohnya audiens ketika mendengar ia membaca puisi. Senyum manisnya masih mengembang ketika ia terjatuh dalam mimpi kemenangan seorang penyair.(Bersambung ke page berikut)