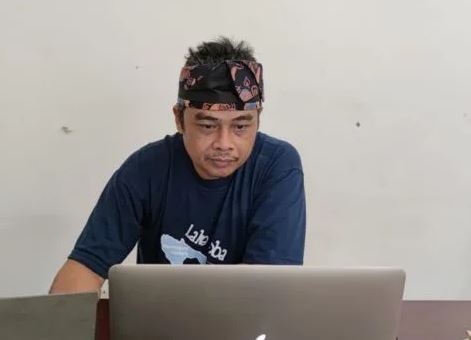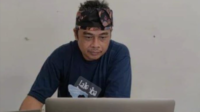Oleh : Musri Nauli
Dalam hiruk-pikuk wacana pembangunan dan konservasi yang seringkali didominasi oleh pendekatan teknis-ilmiah, kita kerap melupakan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem pengetahuannya sendiri—sebuah epistemologi yang terbentuk melalui interaksi panjang dengan alam dan sesama (Soelaiman, 2019).
Bagi masyarakat Gambut Jambi, sistem pengetahuan ini terangkum rapi dalam Seloko. Bukan sekadar pepatah. Tetapi fondasi cara mereka memahami realitas, membedakan benar-salahn dan merumuskan kehidupan yang berkelanjutan.
Memahami Seloko bukanlah romantisme masa lalu, melainkan sebuah keharusan intelektual dan praktis (Soelaiman, 2019).
Jembatan untuk menyelami logika pengetahuan komunitas yang telah terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem gambut selama berabad-abad.
Dalam setiap Seloko, terkandung tiga lapisan nilai yang saling bertaut. Etika, estetika dan makna
Panduan Hidup yang Holistik
Seloko berfungsi sebagai kerangka etika yang sophisticated (rumit). Prinsip seperti “Alam sekato Rajo. Negeri Sekato Batin” menempatkan alam sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,
Sementara manusia adalah bagian darinya. Bukan penguasanya (Acmadi, 2008). Inilah fondasi etis yang menuntun setiap tindakan. Dari membuka lahan hingga menyelesaikan sengketa.
Larangan adat seperti “Petai dak boleh ditutuh. Durian dak boleh dipanjat” bukanlah aturan sembarang, melainkan cerminan pemahaman ekologis mendalam yang mencegah eksploitasi berlebihan (Rozak & Arifuddin, 1423 H).
Bahkan sanksi spiritual seperti “Keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berakar. Ditengah ditarik kumbang padi, Padi ditanam ilalang tumbuh. Dimana juga mungkirnya disanalah tinggallah sumpah itu”, (Kutukan Datuk Paduko Berhalo), Kualat atau Plali (pengucilan) beroperasi pada tingkat keyakinan terdalam menunjukkan bahwa etika Seloko tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga menyentuh dimensi batin dan spiritual (Yulianto, 2018).
Estetika dalam Seloko
Seloko tidak hanya berbicara tentang benar-salah tetapi juga tentang keindahan dan harmoni.
Ungkapan seperti “”Bulat aer karena pembuluh, bulat kato oleh mufakat” (menjaga keindahan dunia) mencerminkan nilai estetika yang memandang keindahan dan keteraturan sebagai tujuan moral itu sendiri (Sunarto, t.th.). Estetika ini terwujud dalam tata kelola sosial yang rapih—seperti musyawarah mufakat (“Bulat aer karena pembuluh, bulat kato oleh mufakat”)—yang tidak hanya efektif, tetapi juga indah dalam kerapihan dan keselarasannya (Nopriyandri, 2018).
Bahasa Seloko yang puitis dan penuh kiasan juga menunjukkan bahwa kebijaksanaan disampaikan bukan dengan instruksi kaku, tetapi melalui keindahan tutur yang meresap ke dalam sanubari.
Makna Simbolik – Lapisan Makna yang Berlapis
Setiap kata dalam Seloko adalah simbol yang membawa makna berlapis. “Bak aur dengan tebing” bukan hanya menggambarkan hubungan saling mendukung antara bambu dan tebing, tetapi merupakan simbol mutualisme dalam masyarakat (Peirce, 1932).
“Durian takuk rajo” bukan sekadar penanda batas fisik, melainkan simbol kedaulatan hukum adat yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi (Data Etnografi Masyarakat Gambut Jambi, 2024). Bahkan tanda alam seperti “akar bekait, pakis, jelutung” adalah simbol penanda ekologis yang lebih akurat daripada angka kedalaman gambut versi negara (Nauli, 2024).
Makna-makna ini tidak statis; ia hidup, berkembang, dan terus ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman (Peirce, 1932).
Membongkar Makna Simbolik: Perlunya Pendekatan Multidisiplin
Untuk sepenuhnya menghargai kedalaman makna simbolik dalam Seloko, kita tidak dapat mengandalkan satu sudut pandang ilmu saja. Diperlukan perpaduan perangkat keilmuan yang komprehensif.
Filsafat (khususnya cabang Epistemologi, Aksiologi, dan Ontologi, untuk menggali sumber pengetahuan, sistem nilai, dan cara masyarakat mendefinisikan realitas (Soelaiman, 2019; Bakhtiar, 2012).
Semiotika (khususnya model triadik Charles Sanders Peirce (Representamen-Objek-Interpretan) dan semiotika kultural Roland Barthes, untuk membedah struktur tanda, lapisan makna (denotasi-konotasi-mitos), serta ideologi yang tersembunyi di balik simbol (Budiman, 2011; Barthes, 2007).
Antropologi Budaya dan Hukum Adat untuk memahami konteks sosio-kultural, fungsi institusional, dan mekanisme penegakan norma dalam komunitas (Koentjaraningrat, 2009; Supian dkk., 2018).
Ekologi Politik dan Ilmu Lingkungan, untuk menganalisis relasi kuasa, konflik pengetahuan, dan efektivitas kearifan ekologis yang terkandung dalam Seloko (Robbins, 2004; Maknun, 2017).
Hanya dengan pendekatan multidisiplin inilah kita dapat melihat Seloko bukan sebagai warisan budaya yang statis. Melainkan sebagai sistem pengetahuan yang hidup—sebuah epistemologi konservasi komunal yang menawarkan solusi nyata bagi krisis ekologis dan sosial yang kita hadapi hari ini.
Dalam setiap Seloko bukan hanya tersimpan kata-kata. Tetapi sebuah renungan untuk merendahkan hati, belajar dari kearifan yang telah teruji waktu dan mengakui bahwa keberlanjutan sejati justru terletak pada kesediaan kita untuk mendengarkan suara dari atas gambut. (*)
Advokat. Tinggal di Jambi